Sejak pertama kali aku ngeblog tahun 2008, aku hampir gak pernah bahas politik. Bahkan waktu ada tawaran menulis tentang tokoh politik di blog-ku, aku tolak. Rasa-rasanya itu bukan ranahku sih. 🙂
Tapi kali ini beda. Karena yang terjadi bukan sekadar “isu politik”. Ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan menurutku, yaitu: pembiaran.
Bermula dari wacana kenaikan gaji DPR yang bikin banyak orang naik darah. Terlebih hal tersebut dibicarakan di era ‘in this economy’, yang mana terjadi banyak PHK dan sebagainya.
Kemudian saat demonstrasi, jatuh korban jiwa, yaitu Affan Kurniawan. Seorang anak muda, ojol berusia 21 tahun, tewas terlindas atau dilindas oleh kendaraan taktis Brimob. Dia bukan demonstran. Dia cuma lagi cari nafkah, terjebak di tengah kerumunan.
Nyawa melayang di tengah wacana kenaikan gaji. Ironi. Wajar aja kalau kita marah. Dan amarah ini sah. 🙂
Tapi di persimpangan ini, aku juga takut arah amarah kita jadi salah
Aku bisa mengerti orang turun ke jalan. Bisa mengerti orang bersuara lantang. Itu hak. Tapi aku juga lihat sisi lain yang menyesakkan dada: toko-toko di Senen dijarah, halte TransJakarta dibakar, gedung DPRD Makassar hangus dan menelan korban.
Di titik tersebut aku mikir: “Menjarah toko gak bakal memotong gaji DPR. Itu cuma bikin sesama rakyat kecil tambah luka.”
Jujur, aku percaya banget pada kekuatan suara kolektif. Tapi aku juga gak bisa pura-pura setuju kalau amarahnya salah arah. Karena saat itu terjadi, mereka yang masyarakat lawan justru menang dengan cara lain: narasi perjuangan jadi ternodai.
Kita punya kebebasan memilih untuk jadi orang yang seperti apa
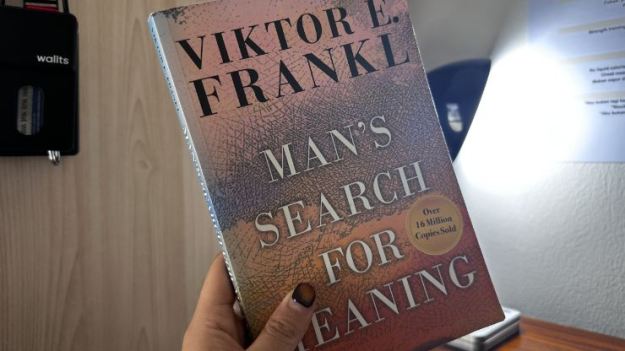
Viktor Frankl pernah bilang, di antara stimulus dan respons, selalu ada ruang. Dan di ruang itulah, kita punya kebebasan untuk memilih.
Aku suka banget bagian ini. Karena rasanya relevan banget sama kondisi sekarang. Amarah itu stimulusnya. Tapi respons kita – itulah yang akan menentukan cerita apa yang kita wariskan.
Aku jadi ingat kalimat Frankl yang lain: “No group consists entirely of decent or indecent people.” Diceritakan dalam chapter pertama buku tersebut, ada sipir dalam kamp konsentrasi Nazi yang memilih memberikan sepotong roti kepada tahanan Jewish.
Hari ini pun sama.
Ada aparat yang tetap tancap gas, tapi ada juga yang menolong korban.
Ada massa yang melempar batu, tapi ada mahasiswa yang sibuk bagi logistik untuk aksi damai.
Ada ribuan ojol, karyawan, UMKM, dan bahkan pengusaha yang mencari nafkah buat keluarganya.
Di ruang batas antara marah dan bertindak, kita selalu punya pilihan.
Gimana caranya biar amarah bukan jadi peluru nyasar?
Aku tahu, kita gak mungkin pura-pura gak marah. Dan gak sehat juga kalau kita paksa redam. Tapi amarah bisa diarahkan. Supaya menjadi energi, bukan peluru nyasar.
1. Belajar kasih jeda dan mikir dulu
Kadang kita butuh berhenti sejenak. Tarik napas sebelum klik “share” suatu berita. Tanya ke diri sendiri: “Ini malah memperkeruh atau nge-share sesuatu yang bermanfaat?”
Jadi gak sekadar share dan share tanpa memverifikasi dulu kebeneran dan ketepatan dari isi berita ataupun postingan tersebut.
2. Cari medan perjuangan yang cocok buatmu
Gak semua orang harus teriak di jalan. Ada yang kuatnya di tulisan, ada yang bikin karya, ada yang edukasi circle-nya. Kalau aksinya selaras sama diri, amarah kita gak cuma jadi ledakan sesaat, tapi diharapkan menjadi api yang terus bertahan atau sustain.
3. Jaga narasi agar gak melenceng dan ‘salah tulis’
Orang lebih gampang ingat yang dramatis. Sayangnya, itu berarti penjarahan lebih cepat masuk ke memori publik daripada aksi damai.
Kalau dibiarkan, sejarah bisa saja salah menuliskannya jadi: “demonstrasi anarkis”, padahal tujuannya mulia. Itu sebabnya narasi harus dijaga, supaya gak dibajak.
4. Ingat bahwa amarah itu bukan diri kita
Thích Nhất Hạnh pernah bilang: “Anger is not you.”
Kalimat sederhana, tapi ngena banget. Marah itu kayak tamu: dia datang, dia pergi. Tapi amarah bukan kita.
Bedanya besar lho antara bilang “Aku sedang marah” sama “Aku adalah marah.”
Kalau kita melihat marah sebagai sesuatu di luar diri, kita bisa mengasuhnya, bukannya dikuasai. Kayak merawat bayi nangis: didengar, ditenangkan, diarahkan.
Being calm bukan berarti diam, tapi melakukan sesuatu dengan pemahaman
Aku percaya, being calm bukan berarti kita pasif. Being calm artinya kita tahu kapan harus bicara, kapan perlu menahan diri, dan kapan memberi ruang untuk orang lain yang juga berjuang dengan caranya.
Solidaritas bukan berarti semua orang melakukan hal yang sama. Solidaritas berarti kita saling jaga – supaya suara kita gak hilang karena provokasi, dan supaya energi kita tetap jadi kekuatan, bukan senjata yang menyasar ke sesama.
Empat hal tadi yang aku sebutkan sebelumnya; memberi jeda, memilih medan perjuanganmu, menjaga narasi, dan ingat bahwa amarah bukan diri kita – bisa menjadi semacam kompas kecil. Bukan untuk menjanjikan keadaan sudah pasti membaik, tapi supaya kita gak kehilangan diri sendiri di tengah ketidakpastian.
Karena jujur aja, kita gak tahu negara ini bakal seperti apa. Kita gak bisa janji kalau kondisi bakal segera mereda. Atau… kalau yang bobrok bakal bisa cepat berubah. Tapi yang pasti, hal yang bisa kontrol adalah diri kita dan mental kita. Kita bisa bilang ke diri sendiri: “Aku boleh marah, tapi aku gak bakal biarin amarah itu merusak aku.”
Dan mungkin itu cara paling realistis buat bertahan: bukan dengan kepastian bahwa keadaan bakal membaik, tapi dengan memilih buat tetap utuh, walaupun keadaan di luar kacau. 🥲







Leave a comment